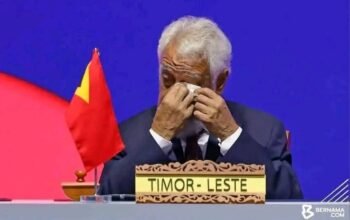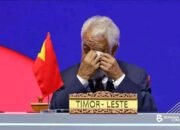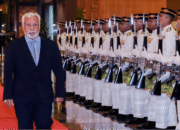LITERATURA AKADEMIKA, (LIBERDADETL.com) — Artikel ini ditulis sebagai bagian dari kajian kritis terhadap fenomena sosial yang selama dua dekade terakhir menjadi bagian dari dinamika keamanan dan budaya komunitas di Timor-Leste, yakni organisasi bela diri dan ritual spiritual seperti PSHT, Kera Sakti, KORK, dan kelompok 7-7. Penulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi secara ilmiah dan kontekstual bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengaktifkan kembali kelompok-kelompok ini dapat dijadikan sebagai strategi transformasi sosial, bukan sekadar pendekatan penertiban hukum.
Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, dan hukum, serta merujuk pada penelitian terdahulu seperti studi António Soares (2015) mengenai kekerasan antar kelompok bela diri di Dili, teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi (1969), hingga konsep restorative justice oleh Howard Zehr (1990), artikel ini menyajikan pemikiran berbasis data, bukan spekulasi. Harapannya, tulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan, akademisi, lembaga keagamaan, dan masyarakat umum dalam memahami potensi positif dari organisasi bela diri jika dikembangkan secara edukatif, legal, dan spiritual.
Di tengah dinamika sosial Timor-Leste yang terus bergerak pasca kemerdekaan, negara kini menghadapi tantangan besar dalam mengelola warisan-warisan komunitas yang pernah dianggap kontroversial. Organisasi bela diri seperti PSHT, Kera Sakti, KORK, hingga komunitas spiritual 7-7, dulunya identik dengan konflik, rivalitas, bahkan kekerasan. Namun dalam kebijakan terbaru, pemerintah tidak memilih jalan pembubaran atau penindasan. Sebaliknya, negara hadir dengan satu pilihan: mengatur yang liar, dan menghidupkan yang luhur. Artikel ini membongkar secara kritis dan mendalam bagaimana seni bela diri bertransformasi dari alat kekuasaan informal menjadi instrumen edukasi, olahraga, dan spiritualitas, sekaligus menelusuri bagaimana negara, gereja, dan masyarakat sipil dapat bersinergi dalam menjadikan kekuatan tubuh sebagai kekuatan kebangsaan.
i. Legalisasi seni bela diri di timor-leste: perpaduan strategis antara budaya dan regulasi negara
Langkah Pemerintah Timor-Leste dalam merumuskan kebijakan pengaktifan kembali organisasi bela diri seperti Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Kera Sakti, KORK, dan komunitas ritual 7-7, mencerminkan upaya sistematis dalam merekonstruksi nilai-nilai warisan budaya menjadi alat pembangunan sosial. Pendekatan ini mencerminkan konsep “soft power domestik” sebagaimana dijelaskan oleh Joseph Nye (2004), ahli ilmu politik dari Harvard University, bahwa kekuatan budaya dan nilai lokal dapat diolah menjadi alat transformasi sosial yang tidak koersif.
Legalitas ini tidak dimaknai sebagai legitimasi kekuasaan atas ruang publik, namun sebagai pemberian kerangka hukum yang memungkinkan aktivitas komunitas berlangsung secara teratur, terukur, dan terkendali. Dengan instrumen perundang-undangan yang tengah disusun oleh Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Menteri, negara memainkan fungsi sebagai pelindung hak asasi warga sekaligus sebagai pengarah sosial.
Seni bela diri, dalam konteks antropologis, bukan hanya bentuk pertahanan diri, tetapi juga media internalisasi nilai-nilai luhur. Menurut Clifford Geertz (1973), antropolog asal AS, budaya adalah sistem simbolik yang dihidupi masyarakat. Dalam praktik silat, simbol seperti salam hormat, seragam, dan tata gerak menciptakan sistem nilai yang menginternalisasi kesetiaan, kesopanan, dan ketekunan.
Latihan bela diri membantu pembentukan struktur mental yang disiplin. Jean Piaget (1952), psikolog kognitif dari Swiss, menjelaskan bahwa perkembangan moral anak dan remaja terbangun dari interaksi sosial yang terstruktur. Latihan teratur di dalam organisasi bela diri memungkinkan pengembangan moralitas yang lebih tinggi, terutama melalui hubungan hierarkis antara pelatih dan murid.
Di sisi lain, organisasi seperti PSHT turut memperkuat identitas budaya dengan pendekatan historis. Nilai-nilai silat yang mengakar pada filosofi Jawa, seperti “sepi ing pamrih rame ing gawe” (bekerja tanpa pamrih) diterjemahkan ke dalam bentuk tindakan kolektif dan loyalitas kepada kelompok.
ii. Kontrol sosial dan regulasi negara: sinergi antara masyarakat dan aparat
Negara modern memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam penegakan hukum, namun juga dalam pencegahan konflik horizontal. Menurut teori “kontrol sosial informal” oleh Travis Hirschi (1969), keterikatan individu kepada keluarga, komunitas, dan institusi berfungsi menahan dorongan untuk melanggar norma.
Oleh karena itu, negara perlu membangun sistem regulasi yang partisipatif dengan elemen-elemen berikut:
- Verifikasi Identitas Organisasi – Registrasi legal dengan kode etik berbasis Undang-Undang.
- Kolaborasi Multi-Sektor – Melibatkan Dinas Pendidikan, Gereja, dan LSM untuk memastikan integrasi nilai sosial.
- Sistem Evaluasi Berkala – Audit kegiatan oleh satuan pengawasan sipil dan PNTL.
Kerja sama erat dengan Kepolisian Nasional Timor-Leste (PNTL) sangat vital. Kepolisian tidak boleh bertindak represif, melainkan edukatif dan mediatif. Berdasarkan pendekatan community policing yang dikembangkan oleh Herman Goldstein (1979), efektivitas polisi dalam mengelola konflik sosial bergantung pada kemitraan aktif dengan masyarakat sipil.
Transformasi bela diri ke dalam format olahraga nasional sejalan dengan konsep pedagogi tubuh (body pedagogy) yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu (1990), sosiolog asal Prancis. Ia menekankan bahwa latihan fisik tidak sekadar membentuk tubuh, tapi juga menciptakan habitus atau pola perilaku sosial tertentu.
Olahraga bela diri mengajarkan keteraturan, strategi, dan kendali emosi. Jika dikembangkan sebagai cabang olahraga nasional, seperti dalam model Pencak Silat Indonesia di bawah naungan IPSI dan KONI, Timor-Leste memiliki peluang mengangkat nilai-nilai lokal ke kancah internasional — sekaligus menciptakan ruang kompetisi yang sehat.
Sementara itu, komunitas ritual seperti “7-7” menyimpan unsur spiritualitas dalam bentuk doa, meditasi, dan penataan energi dalam tubuh. Ini bisa diselaraskan dengan pendekatan Kristiani dalam theologia corporis (teologi tubuh), sebagaimana ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II (1984) dalam “Theology of the Body”. Tubuh manusia adalah bait spiritual yang dimuliakan, dan aktivitas fisik dapat menjadi bentuk liturgi kehidupan sehari-hari.
Gereja dapat menjadi mitra dalam proses ini, dengan menyelenggarakan pelatihan bela diri yang didahului dengan doa, retret rohani, atau misa pembukaan latihan. Dengan demikian, seni bela diri bukan hanya olahraga tetapi spiritualitas kontekstual.
Tidak bisa disangkal bahwa organisasi bela diri memiliki rekam jejak kelam, terutama dalam bentrokan antar kelompok di masa lalu. Studi oleh António Soares (2015) dari UNTL menunjukkan bahwa konflik internal antar kelompok bela diri merupakan salah satu penyumbang utama ketidakstabilan sosial di distrik urban pasca kemerdekaan.
Namun, risiko ini bisa ditransformasikan menjadi peluang jika dikelola secara sistematis:
- Pendidikan Damai: Integrasi kurikulum non-kekerasan dalam setiap jenjang pelatihan. Paulo Freire (1970), dalam Pedagogy of the Oppressed, menekankan pentingnya pendidikan kritis dalam membebaskan masyarakat dari struktur kekerasan simbolik.
- Mediasi Komunal: Pelibatan tetua adat (lia nain), imam gereja, dan tokoh pemuda dalam deeskalasi konflik lokal.
- Sanksi Progresif: Pengadilan khusus komunitas dapat dibentuk dengan prosedur restoratif, bukan hanya hukuman retributif.
iii. Sinergi dengan PNTL: membangun keamanan partisipatif
Hubungan antara komunitas bela diri dan institusi keamanan seperti PNTL harus dibangun atas dasar transparansi, saling hormat, dan pengakuan atas peran masing-masing. Berdasarkan prinsip restorative justice (Zehr, 1990), keamanan tidak dihasilkan dari ketakutan terhadap aparat, tapi dari rasa tanggung jawab bersama atas ketertiban sosial.
PNTL diharapkan menjadi fasilitator perdamaian dan bukan hanya penegak hukum. Dengan pendekatan ini, polisi bisa menjadi mentor dalam pelatihan bela diri resmi, bahkan menjadi bagian dari pelatihan moral yang diselenggarakan oleh organisasi bela diri. Di negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan, polisi sering bekerja sama dengan dojo-dojo bela diri dalam edukasi generasi muda.
Masa depan bela diri di Timor-Leste tergantung pada kemampuan negara, organisasi, masyarakat, dan gereja dalam menciptakan ekosistem yang seimbang antara regulasi, edukasi, dan spiritualitas. Seni bela diri bukan sekadar warisan, tetapi sarana penciptaan manusia baru yang kuat secara fisik, bijak secara mental, dan teguh secara spiritual.
Transformasi ini tidak utopis. Ia hanya membutuhkan satu hal: kehendak kolektif yang jujur.
Jika di masa lalu seni bela diri dianggap sumber kekacauan, kini ia ditantang menjadi kekuatan pembentuk peradaban. Negara bukan hanya menertibkan, tetapi memberi arah. Gereja bukan hanya menegur, tetapi mendampingi. Dan masyarakat bukan hanya takut, tetapi didorong untuk menjadi bagian dari transformasi. Jalan ke depan tidak tanpa rintangan—konflik mungkin masih mengintai, ego sektarian bisa muncul kapan saja. Namun dengan regulasi cerdas, nilai spiritual yang kuat, dan edukasi damai yang menyentuh akar, organisasi bela diri dapat berubah menjadi ruang pembentukan karakter generasi baru Timor-Leste. Bukan lagi alat perebutan kuasa, tetapi jalan perubahan menuju masa depan yang bermartabat.
Dari: Almerindo Gaudençio Gomes
Peneliti Timor-Leste
Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Referensi Ilmiah:
- Nye, J. S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. PublicAffairs.
- Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. Basic Books.
- Piaget, J. (1952). The Origins of Intelligence in Children. International Universities Press.
- Hirschi, T. (1969). Causes of Delinquency. University of California Press.
- Goldstein, H. (1979). Improving Policing: A Problem-Oriented Approach. Crime & Delinquency.
- Bourdieu, P. (1990). The Logic of Practice. Stanford University Press.
- Yohanes Paulus II (1984). Theology of the Body. Vatican Publishing.
- Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. Continuum.
- Zehr, H. (1990). Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice. Herald Press.
- Soares, A. (2015). Dinâmica Konfrontasaun Grupu Martial iha Dili. Tese UNTL.