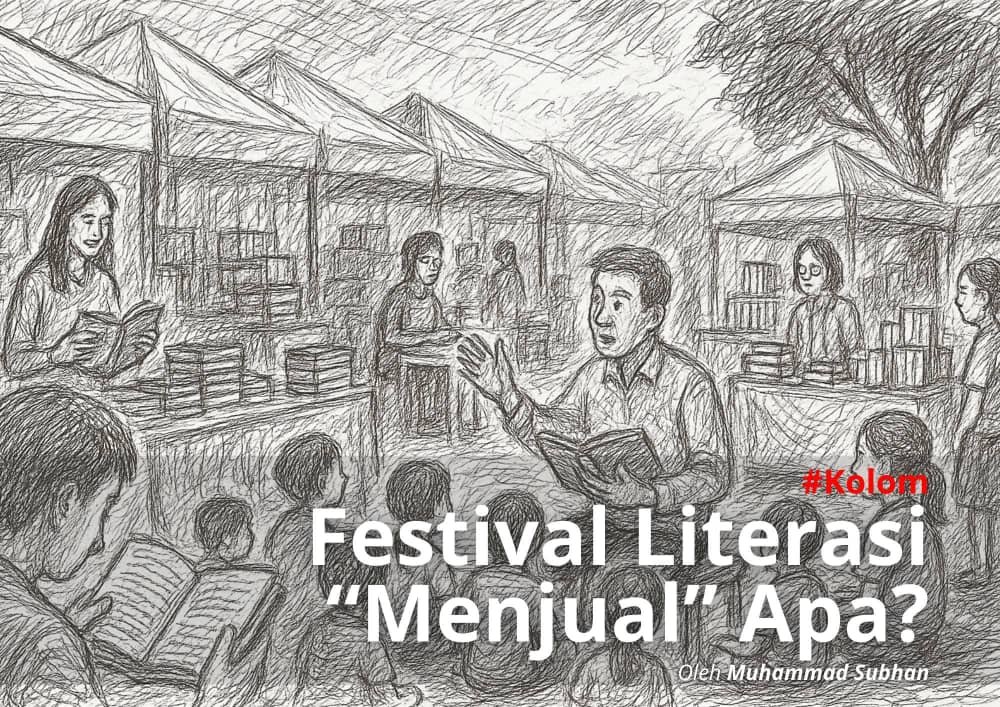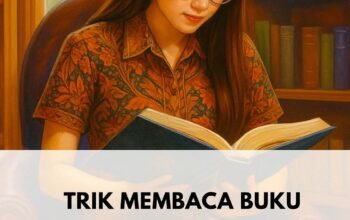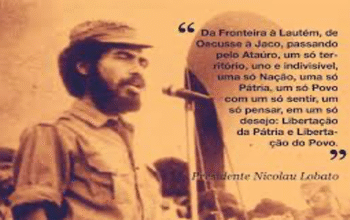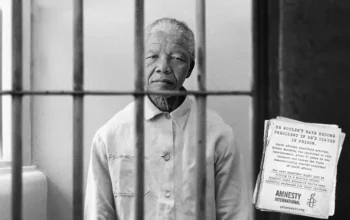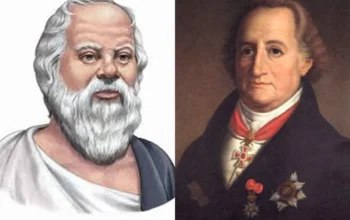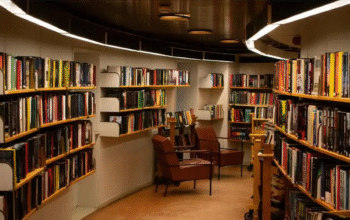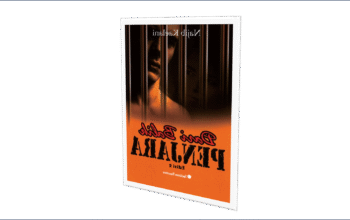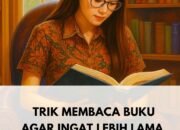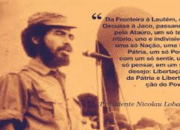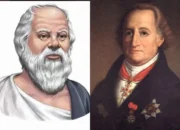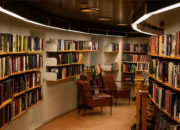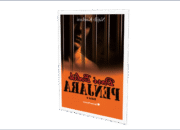LIVRU-KADI KAKUTAK, (LIBERDADETL.com) — FESTIVAL literasi sejatinya dirancang sebagai ruang perayaan gagasan, kreativitas, dan kecintaan masyarakat pada dunia baca-tulis. Namun, dalam praktiknya, tak jarang festival literasi justru bergeser dari ruh awal itu. Yang tampak dominan adalah stand-stand komersial yang lebih menyerupai pasar malam, sementara komunitas literasi yang mestinya menjadi jantung kegiatan literasi sering kali hadir hanya di pojok, bahkan terpinggirkan.
Fenomena ini menunjukkan adanya salah kaprah dalam memaknai festival literasi. Jika ruang yang seharusnya menghidupkan minat baca dan memamerkan karya tulis berubah menjadi ajang jual beli barang konsumtif, maka festival itu kehilangan daya edukatifnya. Memindahkan “isi pasar” ke dalam festival literasi hanya menghasilkan keramaian sesaat, tetapi gagal menumbuhkan kesadaran jangka panjang tentang pentingnya literasi.
Padahal, keterlibatan komunitas literasi sangat vital. Komunitas literasi adalah ujung tombak gerakan membaca di masyarakat. Mereka menyimpan cerita tentang anak-anak yang mulai gemar membaca, tentang warga kampung yang belajar menulis, tentang kelompok ibu rumah tangga yang menghasilkan karya dari kegiatan baca-tulis. Komunitas literasilah yang menjaga bara literasi di tengah masyarakat, bukan stand komersial yang sekadar hadir demi keuntungan dagang sesaat.
Festival literasi sudah semestinya memberi ruang istimewa bagi komunitas-komunitas literasi untuk memamerkan karya, menjual produk literasi, dan berbagi praktik baik. Dengan begitu, festival benar-benar menjadi ajang perayaan literasi yang hidup, bukan sekadar pameran seremonial. Jika festival literasi ingin berdaya, ia harus kembali ke akar: merayakan buku, tulisan, dan kreativitas komunitas. Tanpa itu, festival hanya akan jadi pasar pindahan, atau pasar malam: meriah sesaat tetapi tidak meninggalkan bekas jangka panjang.
Festival literasi yang ideal bukan hanya soal pertemuan fisik, melainkan juga soal pertemuan gagasan. Di sana seharusnya hadir pembaca, penulis, penerbit, guru, pelajar, komunitas, pemerintah, hingga masyarakat umum untuk saling belajar, bertukar inspirasi, dan membangun ekosistem literasi yang berkesinambungan. Workshop menulis, temu penulis dan pembaca, pelatihan literasi digital, bedah buku, peluncuran buku—yang tidak hanya buku-buku karya pejabat—, diskusi lintas generasi, hingga panggung aneka lomba literasi seharusnya menjadi denyut nadi acara.
Kekeliruan yang kerap terjadi dalam festival literasi adalah penyelenggara hanya membuka pendaftaran partisipasi taman bacaan atau komunitas literasi. Pola seperti ini secara tidak langsung membuat ruang partisipasi bersifat pasif: hanya mereka yang tahu dan mampu mendaftar yang akan ikut serta. Akibatnya, banyak kantong literasi di sudut-sudut kampung—yang sesungguhnya kaya dengan praktik baik—tidak hadir karena keterbatasan informasi atau akses.
Festival literasi yang ideal justru harus bersifat “jemput bola”. Penyelenggara wajib turun langsung mendata dan mengundang komunitas-komunitas literasi, sekecil apa pun mereka. Dari taman bacaan yang berdiri di pelosok kampung, lapak baca di pinggir jalan, perpustakaan masjid, hingga kelompok belajar rumah tangga, semuanya adalah potongan mozaik literasi yang tak bisa dipinggirkan. Undangan personal menunjukkan pengakuan dan penghargaan, sekaligus memberi ruang yang setara—tak jarang pula terjadi, dan ini sangat disayangkan, penyelenggara hanya mengundang 1—2 komunitas literasi, menandakan sekadar ada, sementara stand-stand lain diisi UMKM yang tak terkait dengan komunitas literasi.
Melibatkan sebanyak mungkin komunitas literasi di masyarakat, membuktikan bahwa festival literasi tidak hanya menghadirkan wajah kota atau komunitas besar, atau semata mengatasnamakan sebuah forum besar, melainkan juga mewakili keragaman gerakan literasi di seluruh pelosok. Kehadiran mereka bukan sekadar pelengkap, melainkan inti perayaan itu sendiri.
Banyak orang masih menganggap komunitas-komunitas literasi di masyarakat hanya sebatas tempat meminjam dan membaca buku. Padahal, saat ini komunitas-komunitas itu sudah bertransformasi menjadi dapur produksi literasi. Dari bilik kecil mereka lahir banyak produk literasi: buku, permainan edukatif, kerajinan lokal, hingga kuliner khas yang dikemas dengan narasi literasi.
Festival literasi semestinya menjadi etalase yang memamerkan hasil-hasil itu. Dengan demikian, pengunjung festival tidak hanya melihat buku sebagai benda mati, melainkan juga karya hidup yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Produk kreatif yang dipamerkan membuka mata publik bahwa literasi tidak terbatas pada aktivitas membaca buku serius, tetapi juga bisa berwujud permainan kata, seni rupa, hingga cenderamata yang mengandung cerita.
Festival literasi yang ideal juga harus mampu menegaskan literasi sebagai sumber daya ekonomi. Literasi yang berdaya ekonomi bukan sekadar jargon, melainkan praktik nyata: keterampilan membaca, menulis, dan mengelola informasi yang menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.
Komunitas literasi bisa berperan sebagai inkubator ide kreatif. Dari sana lahir buku karya komunitas yang dijual untuk menambah kas komunitas. Ada pula konten digital edukatif yang dipasarkan melalui media sosial. Ada juga kerajinan tangan yang dikemas dengan narasi literasi, misalnya batik dengan motif lokal, atau kopi lokal yang dipasarkan melalui cerita asal-usulnya. Semua itu harus diproduksi komunitas literasi, lalu dibawa ke arena festival literasi.
Festival literasi adalah momentum untuk menghubungkan produk-produk ini dengan publik yang lebih luas. Pameran, penjualan, promosi, hingga jejaring dengan penerbit, donatur, atau pemerintah bisa terjadi di sana. Dengan begitu, literasi bukan hanya memberi manfaat kognitif, melainkan juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan.
Ekosistem literasi yang ideal sesungguhnya bergerak dalam sebuah alur yang saling menguatkan. Komunitas literasi berperan sebagai dapur produksi, tempat ide, karya, dan produk kreatif lahir dari aktivitas harian komunitas. Dari sana, festival hadir sebagai etalase: ruang memamerkan, memasarkan, sekaligus mempromosikan karya-karya yang telah lahir.
Hasil dari festival itu kemudian memberi daya ekonomi bagi literasi, memperkuat komunitas, menambah semangat berkarya, serta mendorong literasi menembus ranah ekonomi kreatif. Dengan demikian, festival literasi tidak berhenti pada euforia sesaat, melainkan ikut menegakkan fondasi ekosistem yang berkelanjutan. Tanpa siklus semacam ini, festival hanya akan menjadi pesta singkat yang gaungnya lenyap seiring bubarnya panggung.
Festival literasi mestinya bukan memindahkan pasar, bukan pula seremonial tahunan yang mengulang pola sama tanpa makna baru. Festival literasi adalah ruang perjumpaan, pengakuan, dan perayaan terhadap karya-karya yang lahir dari komunitas literasi. Penyelenggara festival harus berani mengubah cara pandang: dari sekadar menyuruh komunitas mendaftar, menjadi aktif menjemput dan memberi ruang luas bagi mereka.
Penting diingat, literasi hidup di jantung masyarakat, yang dijaga oleh komunitas-komunitas literasi: lembaga pendidikan formal dan non-formal, taman bacaan, kelompok baca, dan komunitas-komunitas yang terus berjuang dengan segala keterbatasan mereka. Festival literasi yang ideal adalah festival yang mengakui, merangkul, dan menampilkan kerja-kerja kecil namun konsisten itu. Bukan sekadar untuk “gengsi-gengsian”.
Jika festival literasi mampu kembali pada ruh sejatinya, ia tidak hanya akan menjadi pesta, melainkan juga gerakan yang menyalakan api kesadaran membaca dan menulis di tengah masyarakat. Festival semacam itu bukan sekadar merayakan buku, tetapi juga merayakan manusia yang tumbuh bersama literasi. Hanya dengan cara itu, festival literasi akan benar-benar berarti: bukan hanya hingar bingar sesaat, melainkan warisan kultural yang memperkuat peradaban.
Oleh Muhammad Subhan