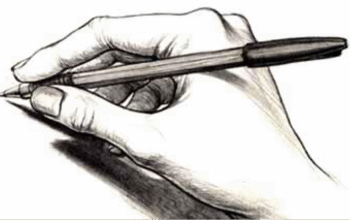ISTÓRIA BADAK, (LIBERDADETL.com) — Di sebuah desa yang sunyi di pinggir danau, jauh dari hiruk-pikuk kota, tinggal seorang pemuda bernama Amino. Rumahnya terbuat dari bambu dan beratapkan rumbia, berdiri di atas tanah warisan yang ditinggalkan ayahnya. Ladang kecil, sebatang pohon mangga tua, dan danau biru yang tenang adalah dunia tempat ia tumbuh.
Amino tinggal hanya bersama ibunya yang sudah tua. Ayahnya telah meninggal sepuluh tahun yang lalu, ketika ia baru berumur lima tahun. Sejak saat itu, ibunya merawatnya seorang diri, dan Amino pun tumbuh menjadi anak yang kuat, tekun, dan penuh rasa hormat. Walau tak punya saudara, Amino tak pernah merasa benar-benar sendiri — karena dalam hatinya, kata-kata ayahnya tetap hidup.
“Anakku, kalau ayah tak lagi di sini, jangan takut hidup sendiri. Percayalah pada adat kita, pada alam, dan pada Tuhan. Mereka akan menjagamu, seperti aku menjagamu dalam doa.”
Kata-kata itu tertanam kuat dalam jiwa Amino. Ia meyakini bahwa adat istiadat, alam semesta, dan Tuhan bukan hanya pelindung, tapi juga penuntun hidup. Ia mengerjakan ladangnya dengan tangan sendiri, membaca cuaca dari arah angin, dan menanam sesuai kalender bintang yang diajarkan leluhurnya. Jika sedang tak di ladang, ia memancing di danau, bukan untuk hiburan, tapi sebagai bagian dari hidup yang menyatu dengan alam.
Namun yang paling berarti dalam hidup Amino bukan hanya kenangan ayahnya, tapi juga suara lembut ibunya setiap malam. Setelah makan malam yang sederhana, mereka duduk di beranda rumah, menatap danau yang tenang di bawah cahaya bulan. Di sanalah percakapan-percakapan suci lahir, seperti api kecil yang menghangatkan jiwa.
Ibu:
“Amino, langit malam ini cerah sekali… seperti mata bapamu dulu. Tenang dan dalam.”
Amino:
“Aku ingat… Bapa suka ajak aku lihat bintang. Katanya, bintang-bintang itu roh leluhur yang menjaga kita.”
Ibu:
“Itu benar, nak. Leluhur kita tidak pernah mati. Mereka tinggal di alam, di pohon, di angin, dan di danau ini. Maka jaga mereka baik-baik. Jangan rusak tanah yang mereka titipkan.”
Amino:
“Ibu… apakah menjaga alam itu juga bentuk ibadah?”
Ibu: (mengangguk pelan)
“Ya, Amino. Kalau kamu jaga alam, kamu sedang menghormati Tuhan. Karena alam ini adalah napas-Nya. Kita tidak perlu bangun gereja mewah, kalau pohon-pohon kita tebang semua, air kita kotori, dan binatang kita siksa.”
Amino:
“Jadi… kalau aku memelihara ladang dengan benar, tidak serakah… itu juga ibadah?”
Ibu:
“Itu pengabdian. Tuhan tidak minta kita jadi orang besar, tapi jadi orang baik. Jadi anak yang tahu berterima kasih.”
Amino:
“Aku kadang merasa sendiri, Bu. Tapi kata Bapa, kalau aku percaya pada adat dan alam, aku tidak akan pernah benar-benar sendiri.”
Ibu:
“Itulah pesan paling dalam dari ayahmu. Dia tahu bahwa adat, doa, dan tanah ini adalah warisan. Bukan untuk disombongkan, tapi untuk dijaga dan diteruskan.”
Amino:
“Bu… bagaimana caranya aku mencintai semua orang, bahkan yang tidak menyukaiku?”
Ibu:
“Dengan tidak membalas kebencian. Cukup doakan mereka. Seperti pohon mangga yang tetap berbuah meski orang melemparnya dengan batu. Cinta itu tidak butuh balasan, nak. Ia hanya butuh keikhlasan.”
Amino:
“Kalau aku gagal suatu hari nanti… apakah Tuhan akan marah?”
Ibu:
“Selama kamu hidup dengan jujur, menjaga yang Tuhan titipkan, dan tidak melupakan pesan-pesan ayahmu… maka kegagalanmu bukan kutukan, tapi pelajaran. Tuhan tidak hitung sukses kita dengan harta, tapi dengan hati yang bersih.”
Tahun demi tahun berlalu. Ketika musim panen gagal melanda desa, ladang Amino tetap hijau. Ia menggunakan pupuk alami dari daun dan kotoran hewan, dan menjual hasil taninya lewat bantuan tetangga yang memiliki koneksi ke kota. Banyak orang mulai heran, lalu datang belajar padanya. Tapi Amino tetap merendah.
“Saya hanya jaga apa yang dipercayakan. Tanah ini, doa ayah saya, dan nasihat ibu saya. Sisanya biar Tuhan dan alam semesta yang atur.”
Ketika ibunya jatuh sakit, Amino merawatnya sendiri. Malam terakhir sebelum ibunya pergi, ia masih sempat berbisik,
“Jangan tinggalkan kebaikanmu, nak… dan jangan lupa… Tuhan itu tidak pernah tidur.”
Dan setelah kepergian ibunya, Amino tetap tinggal. Ia menjadi guru adat, penjaga danau, dan pembisik damai bagi siapa pun yang datang. Ia menolak kekayaan, menolak popularitas, dan memilih untuk hidup di jalan yang sunyi tapi penuh cahaya — seperti yang diajarkan oleh leluhurnya.
Setiap sore, Amino duduk di batu besar di pinggir danau, tempat ayahnya dulu suka duduk. Ia memandang air yang tenang dan berkata dalam hati:
“Saya hidup begini bukan karena hebat. Tapi karena saya percaya… Tuhan dan alam semesta memang tidak pernah salah jalan.”
Berikut adalah kata penutup untuk dongeng bergambar “Doa di Pinggir Danau”:
Cerita Amino adalah cermin dari kehidupan yang sederhana, tapi penuh makna. Ia mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada harta atau kekuasaan, melainkan pada keyakinan, kesetiaan pada adat, kasih kepada alam, dan iman kepada Tuhan.
Dalam dunia yang semakin bising dan tergesa-gesa, Amino memilih jalan sunyi — hidup dekat dengan alam, mencintai sesama, dan menjaga pesan-pesan leluhur dengan rendah hati. Ia tidak mencari sorotan, tapi hidupnya justru menjadi terang bagi banyak orang.
Semoga cerita ini menginspirasi kita semua — untuk hidup dengan hati yang jernih, jiwa yang damai, dan langkah yang setia pada nilai-nilai luhur warisan orangtua dan tanah air kita.
Karena sesungguhnya, mereka yang setia menjaga tanah, adat, dan cinta kasih — sedang menjaga masa depan dunia ini.