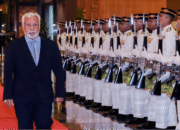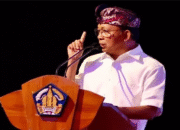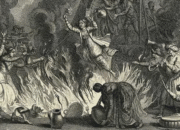NOTÍSIA LITERÁRIA, (LIBERDADETL.com) — Papua adalah cerita yang belum selesai. Bukan karena sejarahnya belum ditulis, tetapi karena kebenaran tentang sejarah itu masih disembunyikan. Dalam lanskap politik modern, ketika kolonialisme dikutuk di forum-forum global, Papua tetap menjadi wilayah yang didefinisikan oleh kekuasaan, bukan oleh kehendak rakyatnya.
Melalui judul “Papua Adalah Koloni”, tulisan ini tidak bermaksud memprovokasi, melainkan mengingatkan: bahwa sejak New York Agreement 1962 hingga tragedi-tragedi berdarah di Nduga, Intan Jaya, dan Pegunungan Tengah, rakyat Papua belum pernah diberi ruang untuk memilih secara bebas, bermartabat, dan sah secara hukum internasional.
Dokumen ini mencoba mengurai realitas sejarah, politik, dan kemanusiaan di tanah yang kaya akan emas tetapi miskin keadilan. Di tengah gempuran infrastruktur dan narasi stabilitas, kami memilih mendengar suara-suara yang selama ini dibungkam oleh dentuman senjata dan dokumen negara.
Enam dekade setelah integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia, isu Papua merdeka tetap membara di tengah klaim pembangunan dan stabilitas nasional. Di balik angka-angka statistik dan proyek-proyek infrastruktur, tersimpan narasi panjang tentang sejarah aneksasi, perlawanan bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, dan solidaritas global yang terus menyoroti satu pertanyaan utama: apakah rakyat Papua pernah benar-benar memilih untuk menjadi bagian dari Indonesia?
Sejarah awal: dari penjajahan Belanda ke tangan Indonesia
Papua Barat—sebagaimana disebut dalam narasi perjuangan—merupakan wilayah jajahan Belanda yang secara administratif terpisah dari wilayah Hindia Belanda lainnya. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Belanda mempertahankan kontrol atas Papua, berargumen bahwa rakyat Papua memiliki identitas etnis dan budaya yang berbeda dari bangsa Indonesia.
Pada tahun 1961, Dewan Papua dibentuk oleh Belanda dan deklarasi kemerdekaan Papua dikibarkan dengan bendera Bintang Kejora dan lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua. Namun pada tahun 1962, di tengah tekanan internasional dan campur tangan Amerika Serikat yang khawatir akan pengaruh Uni Soviet di kawasan, perjanjian New York Agreement ditandatangani. Perjanjian ini menyerahkan administrasi Papua kepada Indonesia lewat PBB, dengan syarat bahwa akan diadakan referendum yang sah (Act of Free Choice).
Namun yang terjadi pada tahun 1969 adalah pelaksanaan referendum yang dikendalikan oleh militer Indonesia, di mana hanya 1.026 orang “wakil rakyat” dipilih dan dikondisikan untuk menyatakan integrasi ke Indonesia. Proses ini dikritik keras oleh banyak pihak internasional sebagai “manipulatif dan tidak demokratis.” Dalam bahasa Papua: “Kami tidak pernah memilih.”
Perlawanan bersenjata dan operasi militer
Setelah integrasi yang dipaksakan, perlawanan rakyat Papua berkembang dalam berbagai bentuk—dari diplomasi hingga perlawanan bersenjata. Kelompok yang paling dikenal adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah eksis sejak 1965, dengan basis di hutan-hutan pedalaman dan perbatasan Papua Nugini.
Indonesia merespons dengan operasi militer berkelanjutan: Operasi Tumpas, Operasi Koteka, dan Operasi Sapu Bersih adalah beberapa nama dari berbagai operasi yang dilaporkan menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia berat. Amnesty International, TAPOL, dan Human Rights Watch telah mendokumentasikan pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, dan pemindahan penduduk secara paksa selama puluhan tahun.
Hingga hari ini, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) terus melakukan serangan terhadap aparat negara, sementara militer Indonesia memperluas operasi ke wilayah pegunungan tengah, termasuk Nduga, Intan Jaya, dan Puncak. Warga sipil menjadi korban utama, dengan ribuan mengungsi tanpa perlindungan.
Gerakan politik dan dukungan Internasional
Di tingkat diplomatik, perjuangan Papua merdeka semakin mendapat panggung global. United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)—sebuah payung organisasi perjuangan damai Papua—berhasil memperoleh status pengamat di Melanesian Spearhead Group (MSG), dan dukungan dari negara-negara Pasifik seperti Vanuatu, Solomon Islands, dan Papua Nugini.
Tokoh-tokoh seperti Benny Wenda, pemimpin ULMWP yang kini berbasis di Inggris, telah membawa isu Papua ke sidang Dewan HAM PBB dan Parlemen Eropa. Dukungan juga datang dari tokoh internasional seperti Desmond Tutu (alm), Noam Chomsky, serta jaringan International Parliamentarians for West Papua (IPWP).
Di Pasifik, gerakan Free West Papua menjadi simbol solidaritas terhadap perjuangan bangsa yang dianggap dijajah di abad modern. Mereka tidak hanya menyoroti pelanggaran HAM, tetapi juga penjarahan terhadap sumber daya alam Papua oleh perusahaan multinasional seperti Freeport McMoRan.
Kondisi terkini: infrastruktur, otonomi, atau penindasan baru?
Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) telah mengucurkan triliunan rupiah ke Papua. Jalan raya, bandara, dan rumah sakit dibangun. Tetapi laporan Komnas HAM dan lembaga gereja menyebut bahwa pembangunan ini tidak menghapus luka kolonial yang masih membekas, apalagi ketika aparat keamanan masih hadir dalam jumlah besar.
Alih-alih menyelesaikan akar masalah politik, pendekatan pembangunan dinilai banyak pihak sebagai “kosmetik keamanan.” Pemekaran provinsi yang terbaru (Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan) juga dikritik sebagai cara untuk memecah kekuatan sosial dan politik rakyat Papua.
Merdeka atau Mati, narasi yang terus hidup
Bagi rakyat Papua, perjuangan bukan hanya tentang bendera atau batas wilayah. Ini soal harkat, martabat, dan hak menentukan nasib sendiri—self-determination—yang telah dijanjikan tapi tak pernah ditepati. Selama hak dasar ini tidak dipenuhi, narasi “Papua Merdeka” tidak akan mati, tapi justru diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Dan di dunia yang semakin terhubung, suara mereka tak lagi bisa dibungkam hanya dengan senjata. Dunia mulai mendengar, meski belum cukup berani untuk bertindak. Papua bukan masalah separatisme, tetapi masalah sejarah yang disangkal dan keadilan yang ditunda.
Hak Asasi Manusia: jeritan yang digelapkan
Laporan tahunan dari Komnas HAM, Amnesty International, dan Human Rights Watch terus menunjukkan bahwa Papua adalah salah satu wilayah dengan indeks pelanggaran HAM tertinggi di Indonesia. Mulai dari pembunuhan terhadap anak-anak dan warga sipil, pengusiran paksa, penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis damai, hingga pembatasan jurnalis internasional masuk ke Papua.
Banyak tokoh gereja Katolik dan Protestan di Papua menyuarakan keprihatinan serupa. Sinode Gereja Kingmi, Dewan Gereja Papua, hingga Uskup Jayapura berulang kali menyerukan dialog damai yang bermartabat, namun suara mereka sering dibungkam oleh narasi nasionalisme Jakarta yang menyamaratakan Papua dengan konflik “kecil” atau “separatisme bersenjata.”
“Kehadiran negara di Papua lebih terasa sebagai kekuatan militer, bukan keadilan sosial,” ujar seorang pastor Katolik dalam kesaksian tertutup kepada tim pencari fakta HAM tahun 2024.
Politik Global: Antara dukungan moral dan diplomasi bungkam
Meski isu Papua mulai menembus forum-forum internasional, banyak negara besar enggan bersuara lantang. Amerika Serikat dan Australia—yang memiliki kepentingan ekonomi di Indonesia, terutama di sektor tambang—cenderung menggunakan bahasa diplomatik yang netral.
Namun berbeda dengan negara-negara Pasifik Selatan. Vanuatu, dalam pidato resmi di Sidang Umum PBB, menyebut Papua sebagai “wilayah pendudukan yang terlupakan dunia.” Solomon Islands dan Tuvalu juga konsisten membawa isu Papua ke dalam organisasi regional dan internasional. Di Inggris dan Eropa, gerakan International Lawyers for West Papua dan Parliamentarians for West Papua semakin aktif menuntut investigasi independen atas pelanggaran HAM dan peninjauan kembali “Act of Free Choice 1969.”
Respons Jakarta: reformasi setengah hati
Pemerintah Indonesia mengklaim telah menjalankan pendekatan “pembangunan damai” dengan pendekatan otonomi, investasi, dan kehadiran negara lewat pemekaran provinsi. Namun, hingga kini, belum ada langkah politik konkret untuk mendengarkan tuntutan dasar rakyat Papua: dialog internasional yang mengakui sejarah yang disangkal.
Beberapa inisiatif seperti dialog Jakarta–Papua yang dirancang LIPI dan gereja-gereja Papua gagal dijalankan secara serius. Komite Khusus Papua di DPR RI pun belum mampu melahirkan satu kebijakan hukum yang mendekatkan keadilan pada rakyat Papua.
Di sisi lain, UU ITE dan stigmatisasi “separatis” digunakan untuk membungkam aktivis damai, bahkan mahasiswa Papua di luar negeri. Demonstrasi damai dengan bendera Bintang Kejora sering berakhir dengan kekerasan dan kriminalisasi.
Kesimpulan: Jalan damai atau jalan panjang menuju referendum?
Hari ini, perjuangan Papua tidak lagi hanya berlangsung di hutan dan pegunungan. Ia hidup di ruang-ruang diplomasi, media sosial, parlemen internasional, dan ruang akademik. Generasi muda Papua kini berani berbicara dalam bahasa hukum internasional dan hak asasi manusia.
Namun selama pemerintah Indonesia belum mengakui akar konflik sebagai konflik politik, bukan sekadar soal ketertinggalan atau pembangunan, maka jurang ketidakpercayaan akan terus melebar.
“Papua tidak sedang mencari belas kasihan. Papua menuntut keadilan sejarah dan hak menentukan masa depannya sendiri,” tegas Benny Wenda di forum parlemen Inggris, April 2025.
Perjuangan ini tidak akan padam hanya dengan infrastruktur dan pemekaran. Seperti kata pepatah Melanesia: “Tanah akan tetap menangis, jika rakyatnya belum bebas.”
Papua bukan hanya masalah keamanan atau pembangunan. Papua adalah soal pengingkaran hak menentukan nasib sendiri, yang selama puluhan tahun dibungkus dalam nama integrasi dan nasionalisme.
Perjalanan dari New York Agreement ke darah yang tumpah di Nduga bukan sekadar rangkaian peristiwa—tetapi cermin dari kegagalan sistemik negara dan dunia internasional untuk mengakui bahwa rakyat Papua berhak menjadi subjek sejarahnya sendiri.
Selama hak dasar itu masih diabaikan, perjuangan Papua akan terus hidup—di hutan, di ruang diplomasi, di mimbar gereja, dan di dada anak muda yang berani mengibarkan bendera Bintang Kejora, bukan sebagai simbol pemberontakan, tetapi sebagai simbol bangsa yang menunggu pengakuan.
Dan jika dunia sungguh membenci kolonialisme, maka inilah waktunya melihat Papua apa adanya: sebuah koloni yang belum dimerdekakan.